Abad 21 menjadi masa dimana percepatan dan akses segala sesuatu menjadi sangat mudah untuk dinikmati bahkan dimiliki, tidak terkecuali pada industri Fesyen.
Beberapa waktu lalu, marak berita mengenai Citayam Fashion Week, sebuah peragaan busana yang dilakukan di tengah jalan oleh berbagai remaja Depok, Citayam, Bojonggede, dan daerah kisaran Jakarta lainnya.
Tentu unik mengingat hal ini menjadi sesuatu yang sangat baru di lakukan di negeri ini, terlebih dilakukan tidak seperti lagam fashion week pada umumnya.
Dahulu, peragaan busana diadakan secara rahasia dan ditujukan khusus untuk kalangan elit. Mereka mengambil bentuk penjualan pakaian dimana para model dengan bangga naik ke panggung untuk memamerkan desain pakaian yang mereka kenakan, namun sekarang format acara ini telah berubah.
Baca Juga : Problematika Sampah dan Nestapa Yang Kita Peroleh
Kini, format pagelaran tersebut berubah dengan kehadiran desainer, kritikus mode, selebritas, serta media yang bertugas untuk memberitakan acara itu. Alhasil, pagelaran fesyen bukanlah sesuatu yang sangat mahal lagi.
Industri Fashion Week
Industri fesyen mungkin bukan yang pertama kali terlintas dalam pikiran sebagai pengguna bahan bakar fosil dalam skala besar. Tetapi, tekstil modern ternyata sangat bergantung pada produk petrokimia yang berasal dari banyak perusahaan minyak dan gas yang turut mendorong emisi gas rumah kaca.
Pada kenyataannya, saat ini industri fesyen menyumbang hingga 10% dari output karbon dioksida global—lebih dari gabungan penerbangan dan pengiriman internasional, demikian paparan the United Nations Environment Programme.
Industri fesyen juga menyumbang seperlima dari 300 juta ton plastik yang diproduksi secara global setiap tahunnya. Poliester sebagai bahan yang sering digunakan dalam fesyen dan mudah ditemukan dimanapun merupakan bentuk plastik berbasis minyak yang telah melampaui kapas sebagai tulang punggung produksi tekstil.
Oleh sebab itu, pakaian yang terbuat dari poliester dan serat sintetis lainnya adalah sumber utama polusi mikroplastik yang sangat berbahaya bagi kehidupan laut.
Saat ini produksi pakaian lebih besar dari yang sebelumnya. Percepatan yang kita alami turut membuat para pelaku dunia fesyen yakni para pengecer dan pelanggan mengaduk-aduk gaya dengan kecepatan yang hingar bingar.
Perkiraan dari McKinsey dan World Economic Forum menunjukkan jumlah garmen yang diproduksi setiap tahun setidaknya naik dua kali lipat sejak tahun 2000.
Adapun dari seluruh produksi yang dibuat tersebut hanya sebagian kecil saja yang akan didaur ulang, 87% dari total input serat yang digunakan untuk pakaian akhirnya dibakar atau dikirim ke tempat pembuangan sampah.
Hal ini membuat banyak merek fesyen mendapat kecaman karena praktik menghancurkan produk yang tidak terjual dan mengirim tumpukan pakaian ke tempat pembuangan sampah di seluruh Global South.
Baca Juga : Upaya Perkuat Pembangunan Berkelanjutan Melalui Indonesian Sustainability Forum 2023
Hal tersebut menjadi sebab industri fast fashion sering disalahkan pada dampak kerusakan lingkungan. Saat ini berbagai merek kelas atas menghasilkan gaya baru dengan bantuan perusahaan mode cepat sehingga melakukan produksi masal dan menghasilkan biaya yang lebih murah.
Dampak Lingkungan Fashion Week
Pasar global untuk benang poliester diperkirakan akan tumbuh dari $106 miliar pada tahun 2022 menjadi $174.7 miliar pada tahun 2032.
Produksi serat poliester tahunan diproyeksikan akan melebihi 92 juta ton dalam 10 tahun ke depan–meningkat 47%. Ada alasan mengapa industri fesyen menyukai poliester sebagai bahan dasar, yakni karena kuat dan serbaguna. Poliester digunakan mulai dari pembuatan pakaian atletik, jaket bulu palsu, bahkan gaun sutra.
Adapun dampak lingkungan dari dominasi poliester dalam industri pakaian menjadi sangat beragam. Pertama, produksi poliester membutuhkan energi yang besar.
Pada 2015, produksi poliester pakaian melepaskan 282 miliar ton karbon dioksida, jumlah ini 3 kali lebih banyak dari kapas. Selanjutnya, kain sintetis seperti poliester kehilangan potongan kecil plastik setiap kali dicuci dan dipakai.
Partikel plastik yang disebut mikroplastik ini mencemari lautan, air tawar, daratan, serta menjadi ancaman bagi hewan yang mengkonsumsinya sebab dapat menghambat pertumbuhan dan reproduksi. Para ilmuwan Australia memperkirakan bahwa terdapat 9,25 hingga 15,86 juta ton mikroplastik di dasar laut.
Survei Geologi AS menemukan bahwa 71% mikroplastik yang ditemukan dalam sampel air sungai berasal dari serat. Para ilmuwan memperkirakan bahwa 35% mikroplastik yang ditemukan di lautan dunia dapat ditelusuri bersumber dari tekstil, hal ini menjadikannya sumber polusi mikroplastik terbesar di lautan dunia.
Menurut data dari the U.S. Environmental Protection Agency, orang Amerika menghasilkan lebih dari 13 juta ton limbah pakaian dan alas kaki setiap tahunnya, dimana angka itu naik dari sekitar 1,4 juta ton pada tahun 1960. Sekitar 70% dari pakaian ini berakhir di tempat pembuangan sampah dan hanya 13% yang didaur ulang untuk pakaian baru atau kegunaan lain.
Masalah terkait fesyen ini jelas struktural dan sistemis. Namun kini harapan baru seakan hadir, yakni dengan maraknya praktik mengonsumsi barang bekas yang tentunya masih layak pakai. Hal ini ditengarai sebagai salah satu upaya dalam menginisiasi semangat ‘berkelanjutan’ yang kini menjadi tren hidup tersendiri.
Minat publik selaku konsumen terhadap upaya ‘keberlanjutan’ tidak pernah setinggi ini. Survei dari grup investasi global Swiss Credit Suisse terhadap 10.000 Gen Z dan konsumen milenial di seluruh dunia menghasilkan fakta bahwa setidaknya 65% responden khawatir tentang lingkungan dan hampir 80% lainnya hanya berniat membeli produk yang berkelanjutan. Alhasil lebih dari 40% responden mengatakan mereka percaya bahwa industri fashion tidak berkelanjutan.
Dengan begitu, banyak pakaian memenuhi pasar dalam beberapa tahun terakhir dan pasar barang bekas telah membengkak secara paralel.
Pada kuartal pertama 2018, Poshmark, pasar daring tempat pengguna dapat membeli dan menjual pakaian dan aksesori bekas, melaporkan penjualan sebesar $177 juta. Periode yang sama pada tahun 2020 menunjukkan penjualan pada angka $309 juta, meningkat sebanyak 75%. Meski begitu, tetap terdapat begitu banyak pakaian sisa yang tidak ingin dibeli oleh konsumen.
Sejatinya terdapat perusahaan yang bekerja untuk mengembangkan teknologi terukur yang memanfaatkan limbah tekstil. Ambercycle contohnya, perusahaan rintisan berusia 6 tahun yang berbasis di Los Angeles sedang mengembangkan sebuah teknologi untuk mengambil pakaian lama, menempatkannya melalui serangkaian proses yang memisahkan serat pada tingkat molekuler, dan memulihkannya untuk membuat benang baru.
Mereka beranggapan mengubah limbah tekstil menjadi sesuatu yang bernilai akan mendorong penggunaan kembali dan dapat mengalihkan jutaan ton pakaian dari tempat pembuangan sampah.
Baca Juga : Urgensi Pendidikan Iklim dalam Kurikulum di Indonesia
Kiranya seperti itulah kehidupan modern saat ini. Berbagai perangai layaknya terbang ke luar negeri, menggunakan barang-barang plastik sekali pakai, hingga menggunakan kendaraan pribadi meski hanya sekadar pulang-pergi kerja dikenal luas menyebabkan kerusakan lingkungan.
Namun isu kerusakan lingkungan tersebut luput meninjau terkait pakaian yang tidak banyak diceritakan dampaknya padahal efeknya tergolong dahsyat. Dan, faktor fashion week bisa jadi salah satu pemicu mengapa kita menjadi sangat konsumtif akan perilaku berbusana ini.




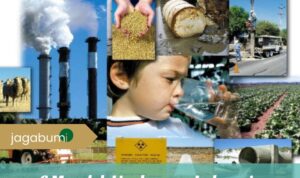



1 comment